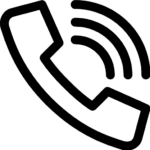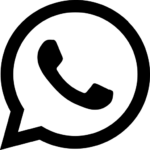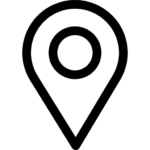[ad_1]

Dalam beberapa referensi kesejarahan ditemukan beberapa orang besar yang lahir pada tahun 1919. Di antaranya adalah satu dari Pakistan dan dua dari Indonesia. Mereka adalah Fazlur Rahman (1919-1988), Harun Nasution (1919-1998), dan K.H. Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur (1919-1991).
Fazlur Rahman adalah seorang pembaharu pemikiran keislaman dari Pakistan yang merupakan lokomotif dan pencetus pemikiran Neomodernisme Islam. Gagasan besar pemikiran ini adalah apresiasi terhadap tradisi (al-turats) dan modernitas (al-hadatsah). Tradisi dalam konsep besarnya—baik ide, gagasan, pemikiran, kaidah berpikir, sistem pengetahuan—yang diwariskan oleh para ulama masa lalu merupakan rujukan (maraji’) penting dalam merekonstruksi pemahaman keislaman kita. Sementara modernitas, yang merupakan produk pemikiran Barat juga mendapat apresiasi positif karena dinilai mengandung seperangkat teori dan gagasan yang membawa ke arah perbaikan umat.
Harun Nasution merupakan intelektual Islam yang menjadi motor penggerak pemikiran rasional di dunia akademik Islam di Indonesia. Mencermati situasi kemunduran umat Islam di berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi (science), ia mengajak umat Islam, terutama insan akademik untuk mengkaji Islam dari berbagai aspeknya. Islam, menurutnya tidak hanya bisa ditinjau dari aspek fiqih saja, tapi juga bisa ditilik dari berbagai dimensi keilmuan Islam, misalnya filsafat (philosophy), ilmu kalam (theology) dan tasawuf (mysticism).
Sementara itu, K.H. Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur adalah pendiri (mu’assis) dan sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Beliau lahir di Kediri pada tahun 1919 dan wafat pada 02 Februari 1991 di Banyuwangi. Meski disinggung dua tokoh pembaharu keislaman sebelumnya, tapi tulisan ini hanya difokuskan pada kontribusi dan peran aktif serta jejak kearifan dari al-Maghfurlah K.H Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur.
Banyak sekali pelajaran kearifan yang dapat dipetik dari beliau dalam memaknai kehidupan ini. Salah satu yang menarik untuk dicermati dan diteladani dari beliau adalah kesederhanaan dan kesahajaan dalam kehidupan sehari-harinya. Potret kesederhanaan dan kesahajaan beliau, menurut penulis, dalam beberapa faktor penting, tidak bisa dilepaskan dari pengamalan langsung dari “kitab” yang diajarkannya kepada para santri. Kitab yang dimaksud adalah Ihya’ Ulumiddin (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama) yang merupakan magnum opus dari seorang sufi besar bernama Abu Hamid Muhammad al-Ghazali al-Thusi.
Beliau dikenal dengan “Hujjah al-Islam,” karena dinilai berhasil mendamaikan pertentangan dan perselisihan antara ulama fiqih dan ulama tasawuf. Al-Ghazali berhasil mensinergikan antara konservatisme ulama fiqih yang literal-tekstual dan ekstremitas kaum sufi yang esoteris-batiniyah dan cenderung mengabaikan syariat.
Magnum Opus al-Ghazali di atas—Ihya’ Ulumiddin—tidak hanya di-ngaji dan dikaji di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat. Termasuk juga di Indonesia, di berbagai Pondok Pesantren yang konsen dan istiqamah mengkhatamkannya secara rutin. Salah satu Pondok Pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, yang saat ini tengah menggelar acara haul pendiri dan pengasuh pertamanya.
Jika diajukan pertanyaan, apa yang bisa diteladani dari beliau? Maka, jawabannya tentu akan sangat beragam sekali, tergantung dari sudut pandang (perspective) mana kita melihat, mencermati dan menganalisisnya. Tapi, memang ada salah satu kearifan beliau yang sangat menonjol, dan ini mungkin menjadi kesepakatan dari para santri senior atau sepuh, yakni kealiman beliau yang terpancar dalam dimensi tasawuf amali/akhlaknya (irfaniyah) dalam mendakwahkan Islam di Nusantara, terutama di bumi Blambangan atau Banyuwangi.
Seorang pemikir Islam kontemporer dari Maroko (Maghribi), Muhammad Abid al-Jabiri dalam magnum opus-nya Trilogi Kritik Akal Arab (Naqd al-‘Aql al-‘Arabi) menyatakan bahwa terdapat tiga epistemologi (sistem pengetahuan) yang perlu diapresiasi dalam upaya memahami Islam yakni, epistemologi bayani, burhani, dan ‘irfani.
Pertama, epistemologi bayani berpijak pada dalil-dalil tekstual seperti Al-Qur’an, Hadits, dan pendapat (qaul) para ulama yang tertuang dalam lembaran-lembaran kitab kuning yang dikaji di pesantren. Kedua, epistemologi burhani merupakan pendekatan yang bertolak dari pengalaman empiris-induktif dan penelitian di lapangan. Ketiga, epistemologi irfani adalah model pendekatan dan penghampiran pemahaman Islam yang berdasar atau bersumber dari ketajaman intuisi (dzauq).
Dalam amatan penulis, model pemahaman keislaman yang didakwahkan oleh Al-Maghfurlah K.H. Mukhtar Syafa’at—atau Mbah Kiai Syafa’at—adalah tidak lepas dari ketiga perspektif pendekatan di atas. Ada beberapa hal atau bukti yang bisa dikemukakan di sini.
Pertama, pendekatan bayani diaplikasikan dalam forum Majelis Musyawarah Pengasuh Pesantren (MMPP). Lembaga ini merupakan forum musyawarah dari para Kiai dan pengasuh pondok pesantren se-Banyuwangi yang bertujuan menjawab berbagai problematika keumatan dan kebangsaan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam menjawab berbagai persoalan tersebut, para Kiai selalu berpegang pada landasan atau dalil-dalil tekstual yang ada, baik di dalam al-Qur’an, Hadits maupun pendapat (qaul) para ulama terdahulu. Ini menjadi bukti bahwa beliau mengaplikasikan epistemologi bayani tersebut.
Kedua, pendekatan burhani terlihat dari upaya beliau ketika mendakwahkan Islam di masyarakat. Dalam berdakwah, beliau tidak hanya bil lisan semata—seperti yang sekarang marak di berbagai media sembari saling menyalahkan dan mengkafirkan—tetapi juga bil hal atau peran aktif seperti, mencermati, mengamati, meneliti, dan terjun langsung dengan melihat kondisi riil sosial kemasyarakatan. Dengan begitu, ajakan dakwah akan terasa sangat mengena dan masyarakat pun dengan legowo mengamininya.
Ketiga, epistemologi irfani yang mengedepankan pendekatan intuisi (dzauq) sangat menonjol dalam diri beliau. Salah satu bukti tak terbantahkan adalah apresiasi beliau yang sangat mendalam terhadap kitab Ihya’ Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali tersebut. Oleh karenanya, tidak heran jika di kalangan para masyayikh, beliau dikenal sebagai “Imam Ghazali”-nya tanah Jawa. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah kitab Ihya’ yang berjalan atau “the living Ihya.” Beliau tidak hanya mengaji (mbalah), tetapi juga mengamalkan apa yang tertera dalam kitab tersebut.
Sinergi dari ketiga pendekatan di atas beliau aplikasikan secara langsung dalam ranah sosial keagamaan secara kontinu dan istiqamah. Di era penjajahan dan awal kemerdekaan, misalnya, sebagai salah seorang santri dari Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU) Hadlratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, beliau menyambut fatwa “Resolusi Jihad” dengan menggerakkan masyarakat mengusir sisa-sisa penjajahan di bumi Blambangan.
Di era Orde Baru, Mbah Kiai Syafa’at terus berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Semangat nasionalisme yang beliau tunjukkan di era penjajahan dan awal kemerdekaan, berlanjut dengan kerja-kerja kemanusiaan di berbagai bidang, di antaranya adalah pendirian dan pengembangan pesantren di era globalisasi.
Dalam suatu halaqah yang dihadiri Kiai-Kiai besar di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, kontribusi pemikiran ditunjukkan oleh Mbah Kiai Syafa’at tentang peranan ulama dan umara dalam membangun bangsa dan negara. Beliau menyatakan bahwa sinergitas antara ulama dan umara sangat dibutuhkan dalam upaya membangun kemajuan bangsa. Ulama berperan di bidang pembinaan moral dan akhlak masyarakat. Sementara umara—dengan kedekatan dan bimbingan ulama—diharapkan dapat menelorkan kebijakan (policy) yang memihak dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Sesuai dengan kaidah fiqih (legal maxims) “tasarruf al-imam ‘ala al-raiyyah manutun bi al-maslahah”.
Apa yang diteladankan oleh beliau—misalnya bersahabat atau perlunya mendekat dengan orang-orang alim dan saleh (ulama)—tersebut sangat relevan, terutama di era sekarang, ketika moralitas sebagian anak bangsa sedang oleng karena keserakahan akan gemerlapnya iming-iming duniawi.
Syaikh Ahmad Ibnu Muhammad Atha’illah al-Sakandari (1250-1309 M), seorang sufi besar dari Iskandariah, Mesir, dalam magnum opus-nya “Syarh al-Hikam” menyatakan “la tashhab man la yunhidluka ila Allah haluh, wa la yadulluka ila Allah maqaluh”. Artinya “Janganlah kau bersahabat dengan orang yang hal-ihwalnya tidak membangkitkan kamu kepada Allah, dan janganlah berteman dengan orang yang ucapan-ucapannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah”.
Dengan mencermati perjalanan hidupnya, ditemukan bahwa Islam memiliki dimensi ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Kesalehan ritual dan sosial sekaligus diteladankan oleh beliau kepada para santri dan masyarakat. Relasi antara Sang Khalik (hablum min Allah) dan makhluk-Nya (hablum min al-nas) harus seimbang (balance).
Peran aktif dan kontribusi positif yang beliau contohkan merupakan teladan bagi kita semua. Dalam Islam, kita mengenal istilah ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah merupakan ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah yang tercantum dalam teks-teks kitab suci-Nya. Sementara itu, ayat kauniyah adalah ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah yang tercermin di alam semesta.
Dalam hal ini, sosok yang penuh kesederhanaan dan kesahajaan Mbah Kiai Syafa’at, menurut penulis merupakan salah satu cermin dari ayat-ayat kauniyah yang ditunjukkan Allah di alam semesta. Inilah yang penulis istilahkan dengan “the living wisdom”. Sebuah nilai-nilai kearifan yang hidup dan memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat kita.
[ad_2]
Source link